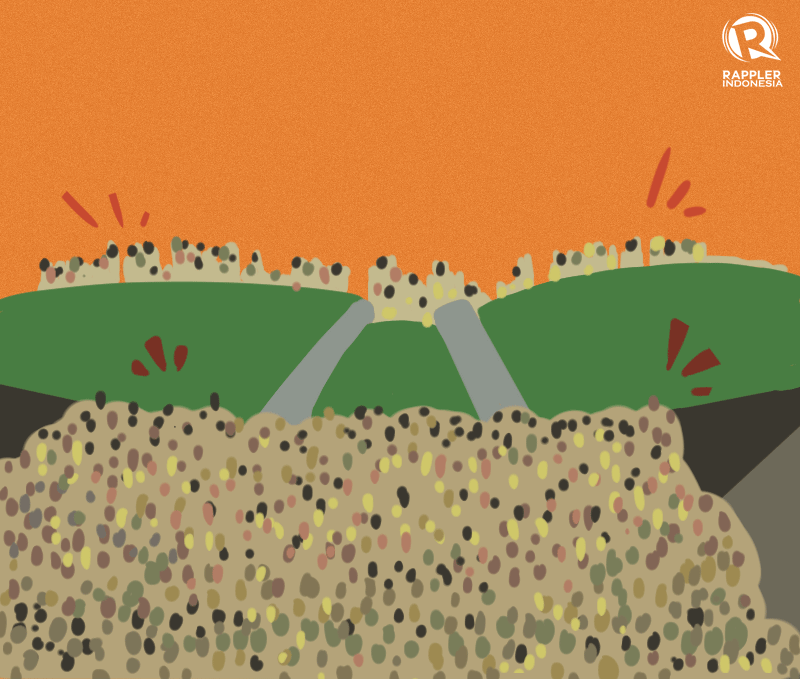Adegan kerusuhan yang terjadi antara mahasiswa dan aparat kepolisian serta tentara masih membekas di ingatan, hingga pengrusakan bangunan dan fasilitas di ibu kota dan pendudukan gedung kura-kura MPR oleh mahasiswa. Puncaknya adalah pengunduran diri penguasa orde baru, Soeharto.
Girang. Itu perasaan saya saat itu. Bagaimana tidak, Soeharto telah berkuasa selama 32 tahun lebih, akhirnya dia lengser juga.
Detik-detik lengsernya Soeharto bisa dilihat di lini masa kamidi sini. Di lini masa itu dituturkan bagaimana mahasiswa berhasil mendesak Soeharto untuk meletakkan jabatannya.
Tapi ternyata, peristiwa Mei 1998 tidak sesederhana itu. Adapuzzle yang kurang lengkap yang harus disusun oleh saya. Maka, saya pun berbincang dengan beberapa aktivis 1998 yang merupakan pelaku sejarah dan jurnalis yang kala itu meliput peristiwa tersebut.
Aksi-aksi mahasiswa di kota-kota di seluruh Indonesia tidak terjadi begitu saja. Tapi itu buah kelompok-kelompok diskusi yang digelar untuk melawan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang dicanangkan oleh Soeharto sejak 1980-an. Lembaga pers di kampus sangat berperan dalam memfasilitasi diskusi-diskusi tersebut.
Awal gerakan mahasiswa
Kepada saya, aktivis mahasiswa 1998 Mugiyanto Sipin menuturkan diskusi itu menjadi gerakan yang lebih rapi karena dipicu masalah yang sangat lokal.
Yakni pada 1993, ada pertemuan paguyuban orang tua/wali mahasiswa di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, tempat Mugi menimba ilmu. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa orang tuanya harus membayar uang gedung Rp 200.000.
Bagi Mugi yang berasal dari Jepara, duit sejumlah itu cukup besar. Apalagi orang tuanya juga harus membayar uang kuliah Rp 180.000. Sumbangan itu dirasa memberatkan dan penggunaannya juga tak transparan. Padahal sepengetahuannya, fakultasnya sudah mendapat alokasi dana dari pemerintah. Untuk apa lagi meminta pada orang tuanya?
Akhirnya Mugi dan teman-temannya mulai mendiskusikan hal ini. Kasak-kusuk ini tidak terhindarkan. Mereka pun sepakat menggelar solidaritas dalam bentuk protes di Fakultas Sastra.
Tanpa disangka, tak sedikit mahasiswa yang mengeluh mengenai uang gedung tersebut. Kemudian solidaritas meluas ke fakultas lain, hingga satu universitas.
Mahasiswa mulai menyadari ada persoalan yang lebih luas, bukan sekedar uang gedung, tapi juga masalah demokrasi di kampus mereka sendiri. Pihak universitas dinilai tidak independen dan suka mendikte.
Suatu hari, mahasiswa di UGM kompak ingin menggelar demo. Tapi aksi mereka tiba-tiba dihadang tentara.
Mahasiswa pun mulai menyadari, ada masalah yang lebih besar lagi selain masalah administrasi. Yakni militerisme di kampus.
Mereka pun mulai berani mendiskusikan ihwal Dwi Fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Mahasiswa kemudian kompak menolak militer masuk kampus.
Setahun kemudian, pada 1994, mereka sepakat membentuk Komite Penegah Mahasiswa (Tegak Lima) yang diketuai Andi Arief.
Komite ini kemudian tidak hanya merangkul mahasiswa di UGM, tapi juga di universitas lain seperti Universitas Negeri Yogyakarta dan Atmajaya.
Akhirnya terbentuklah solidaritas mahasiswa Yogyakarta, yang kemudian berubah menjadi Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) cabang Yogyakarta.
Seperti kembang yang berbunga di musim semi, SMID juga dideklarasikan di Surabaya, Solo, dan kota-kota lainnya. Tapi SMID Yogyakarta tetap menjadi pusat dari gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia.
Untuk pertama kali inilah gerakan mahasiswa yang diawali dengan perasaan senasib sepenanggungan lahir. SMID kelak akan menjadi roh dari perjuangan mahasiswa melengserkan penguasa orde baru Soeharto.
Apakah kita tetap kalah?
Lalu setelah itu tumpahlah gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia. Mereka ramai-ramai mulai berani turun ke jalan. Hampir tiap pekan, mahasiswa berteriak dan mengepalkan tangan.
Aparat pun semakin keras. Bentrok tak terhindari. Hingga jatuhlah korban pertama bernama Moses Gatutkaca. Nama Moses mungkin tak sepopuler nama Mahasiswa Trisakti yang juga meregang nyawa. Moses hampir dilupakan.
Setidaknya itu kesimpulan saya setelah berbincang dengan teman sebaya sesama jurnalis. Ia bahkan tak mengira Moses adalah korban, ia pikir Moses hanya nama jalan di Yogyakarta. Tanpa tahu sejarah di balik penamaan jalan itu. Apakah kamu juga demikian?
Meski demikian, gerakan mahasiswa di tahun 1998 semakin kuat dan meluas. Hingga akhirnya bisa memaksa Soeharto untuk lengser.
Usai penguasa orde baru itu meletakkan jabatannya, di televisi ada adegan mahasiswa bersorak-sorai, sujud syukur, bahkan sampai menggunduli rambutnya.
Tapi perjuangan itu harus dibayar mahal. Setidaknya 14 mahasiswa masih hilang, puluhan lainnya harus meregang nyawa, 150 lebih perempuan Tionghoa diperkosa tanpa kasusnya pernah dibawa ke pengadilan, Rupiah melemah dari Rp 2.000 menjadi Rp 15.000 dalam waktu singkat, dan kerugian material lainnya.
Sementara, di tempat lain, ada sekelompok mahasiswa yang terkejut dengan berita pengunduran diri itu. Mereka adalah aktivis SMID.
Dalam artikel yang saya tulis berjudul Setelah Patung Soeharto Dibakar kekecewaan mahasiswa ini dikonfirmasi oleh aktivis SMID sendiri dan jurnalis senior yang bekerja untuk media asing saat itu.
Menurut mereka, Soeharto memang lengser, tapi tidak sistimnya. Struktur orde baru masih kokoh.
Saya pikir, ada benarnya juga. Sebab baru-baru ini juga, saya menulis artikel Deja Vu Orde Baru. Di situ saya memaparkan tingginya insiden intoleransi yang terjadi di Tanah Air.
Ditambah kejadian yang menimpa saya sendiri saat menjadi pembicara di Asean Literary Festival kemarin untuk sesi Ingat65, platform yang menyediakan ruang untuk anak muda menuturkan kembali tragedi pembantaian massal yang menghilangkan nyawa 1 juta lebih jiwa saat itu.
Pada saat itu, acara yang bertemakan tragedi 1965 diprotes kelompok yang membawa embel-embel Pancasila.
Saya sendiri turun ke lapangan untuk meliput dan berbincang dengan para pendemo. Saya mencoba memahami mengapa mereka menolak acara yang sebenarnya bertemakan pelurusan sejarah ini?
Seorang senior mengingatkan saya bahwa fobia terhadap tragedi 1965 yang sering diidentikkan dengan komunisme ini sudah jadi isu lama. “Basi!” katanya.
Rupanya klausul komunisme kerap digunakan orde baru saat itu untuk melemahkan gerakan-gerakan kritis baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat sipil.
Sebelum 1998 misal, SMID sempat dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena dituding berbau komunis. Anggotanya pun diburu.
Kini, kejadian itu berulang kembali. Gerakan masyarakat sipil yang kritis kembali diusik, diteror, dan coba dibungkam. Mulai dari pelarangan Festival Belok Kiri, pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta karya Rahung Nasution, hingga pelarangan buku-buku kiri yang saya terjemahkan sebagai kritis.
Saya mulai memikirkan kembali, apakah benar kita sudah lepas dari orde baru? Jika iya, mengapa isu komunisme ini dihidupkan kembali hanya untuk memberangus gerakan kritis yang sebenarnya tak ada hubungannya dengan Palu Arit atau Partai Komunis Indonesia atau Marxisme.
Mungkin, kita memang belum menang, mungkin kita masih kalah. Mungkin reformasi yang kemarin sempat kita deklarasikan masih semu. Mungkin Soehartoisme belum mati, ia masih hidup di antara mereka yang menganut paham fasis. Hingga menginspirasi salah satu partai untuk mengusulkannya sebagai pahwalan nasional.
Saat ini, kita hanya bisa menunggu negara mengambil sikap untuk menegaskan dan menindak aparatnya yang sewenang-wenang, sebagai bukti bahwa bangsa ini telah move on dari bayang-bayang Soeharto dan kroni-kroninya yang represif. Sehingga tak ada lagi yang berseloroh, “Piye? Enak jamanku toh?”
sumber: di copas dari Rappler.com